JALAN Maluku 19, Menteng, Jakarta, dua hari sebelum proklamasi. Soebadio Sastrosatomo, kala itu 26 tahun, bertamu ke rumah Sjahrir. Badio, begitu Soebadio biasa disapa, adalah pengikut Sjahrir yang setia. Kelak keduanya bersama-sama mendirikan Partai Sosialis Indonesia. Siang terik. Badio haus luar biasa. Sjahrir menawari anak muda itu minum, tapi Badio menolak. Itu hari di bulan Ramadan: Badio sedang puasa.
Ada yang tak biasa pada Sjahrir hari itu: rautnya sumpek. Sebelumnya, si Bung baru saja bertemu dengan Soekarno, yang mengajaknya bermobil keliling Jakarta. Di jalan, Soekarno mengatakan tak secuil pun ada isyarat Jepang akan menyerah. Soekarno ingin membantah informasi yang dibawa Sjahrir sebelumnya bahwa Jepang telah takluk kepada Sekutu.
Sjahrir mengatakan ini sebelum Soekarno-Hatta berangkat ke Dalat, Vietnam, untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara. Sjahrir berkesimpulan tak ada gunanya berunding dengan Jepang. Pada 6 Agustus 1945, Jepang toh telah luluh-lantak oleh bom atom Sekutu.
Mengetahui Bung Karno tak mempercayainya, Sjahrir berang. Ia menantang Soekarno dengan mengatakan siap mengantar Bung Besar itu ke kantor Kenpeitai, polisi rahasia Jepang, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, untuk mengecek kebenaran informasi yang ia berikan. Sjahrir mengambil risiko: di kantor intel itu ia bisa saja ditangkap.
Tapi Soekarno menolak. Ia yakin Jepang belum menyerah. Itulah yang membuat Sjahrir marah meski ia tak menyampaikannya secara terbuka kepada Bung Karno.
Kepada Badiolah murka itu dilampiaskan. "Sjahrir mengumpat Soekarno man wijf, pengecut dan banci," kata Badio dalam Perjuangan Revolusi (1987). Menurut Badio, itulah marah paling hebat Sjahrir sepanjang persahabatan mereka.
Soekarno tahu Sjahrir sering memakinya. Dalam biografi karya Cindy Adams, Soekarno mengatakan Sjahrir menyalakan api para pemuda. "Dia tertawa mengejekku diam-diam, tak pernah di hadapanku. Soekarno itu gila... kejepang-jepangan... Soekarno pengecut."
Sehari sebelum Badio berkunjung, 14 Agustus 1945, Sjahrir dan Hatta menemui Soekarno di rumahnya di Pegangsaan Timur 56 dan meminta Bung Karno segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Soekarno berjanji mengumumkan proklamasi pada 15 Agustus setelah pukul lima sore. Sjahrir segera menginstruksikan para pemuda mempercepat persiapan demonstrasi. Mahasiswa dan pemuda yang bekerja di kantor berita Jepang, Domei, bergerak cepat menjalankan instruksi itu.
Tapi Sjahrir mencium gelagat Soekarno tak sepenuh hati menyiapkan proklamasi. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, badan yang bertugas menyiapkan kemerdekaan sesuai dengan permintaan Jepang, tak menunjukkan gelagat akan berhenti bekerja.
Panitia misalnya mengagendakan sidang pertama 19 Agustus 1945. Soekarno ketua dan Hatta wakil dalam panitia ini. "Ini akal-akalan Jepang," kata Sjahrir dalam Renungan dan Perjuangan. Sjahrir mengusulkan proklamasi tak menunggu Jepang. Proklamasi, kata Sjahrir, bentuk perlawanan terhadap Jepang. Inilah saatnya melancarkan aksi massa. "Aku penuh semangat. Aku yakin saatnya telah tiba. Sekarang atau tidak sama sekali," kata Sjahrir.
Pukul lima sore 15 Agustus itu, ribuan pemuda berkumpul di pinggir kota. Mereka siap masuk Jakarta segera setelah proklamasi. Begitu proklamasi disiarkan, pemuda akan langsung berdemonstrasi di Stasiun Gambir. Domei dan Gedung Kenpeitai akan direbut. Ternyata, pukul enam kurang beberapa menit, Soekarno mengabarkan belum akan mengumumkan proklamasi. Soekarno menundanya sehari lagi.
Kabar ini membuat ribuan pemuda pengikut Sjahrir marah. Sjahrir menduga polisi rahasia Jepang tahu rencana proklamasi. Para pemuda mendesak proklamasi diumumkan tanpa Soekarno-Hatta. Tapi Sjahrir tidak setuju. Ia khawatir konflik akan terjadi di antara bangsa sendiri.
Tapi kabar bahwa proklamasi batal diumumkan tak sempat dikabarkan ke Cirebon. Pemuda di Cirebon di bawah pimpinan dokter Soedarsono-ayah Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono-hari itu juga mengumumkan proklamasi versi mereka sendiri. Mereka mengatakan tidak mungkin menyuruh pulang orang yang telah berkumpul tanpa penjelasan.
Pada 15 Agustus tengah malam, Badio menemui Sjahrir. Badio mendesak Sjahrir membujuk Soekarno dan Hatta segera mengumumkan proklamasi. Sejam kemudian, Badio menemui kembali Sjahrir. Tapi, dari Sjahrir, kabar tak enak itu didengar Badio: Dwitunggal menolak menyampaikan proklamasi meski Sjahrir telah mendesak.
Pemimpin pemuda lalu pergi. Menurut Badio, mereka bertemu di Cafe Hawaii, Jakarta. Di sini mereka memutuskan untuk menculik Soekarno. Keputusan ini juga melibatkan kelompok lain, di antaranya Pemuda Menteng 31, seperti Wikana, Chaerul Saleh, dan Soekarni, serta dokter Moewardi dari Barisan Pelopor.
Sekitar pukul dua dinihari, Badio datang lagi ke Sjahrir. Ia mengusulkan penculikan Soekarno. Sjahrir tak setuju. Ia menjamin, besoknya bisa memaksa Bung Besar membaca proklamasi.
Badio pergi. Tapi satu jam kemudian ia kembali, membangunkan Sjahrir, dan mengabarkan bahwa sekelompok pemuda nekat menculik Soekarno-Hatta. Sjahrir meminta, apa pun yang terjadi, di antara mereka jangan bertikai. Yang paling penting, kata Sjahrir, proklamasi harus diumumkan secepatnya. Soekarno dalam otobiografinya menyebut Sjahrir penghasut para pemuda. "Dialah yang memanas-manasi pemuda untuk melawanku dan atas kejadian pada larut malam itu," kata Soekarno.
Dalam buku Sjahrir karangan Rudolf Mrazek (1994), Sjahrir disebut-sebut sebagai orang yang menganjurkan Soekarno dibawa ke Rengasdengklok, Jawa Barat-markas garnisun pasukan Pembela Tanah Air.
Ahmad Soebardjo, yang dekat dengan Soekarno, memberi tahu pemimpin Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang Laksamana Tadashi Maeda tentang penculikan itu. Maeda memerintahkan anak buahnya, Nishijima, mencari Wikana di Asrama Indonesia Merdeka. Nishijima dan Wikana bertengkar hebat. Nishijima memaksa Wikana memberi tahu tempat Soekarno-Hatta disembunyikan. Imbalannya: Maeda dan Nishijima akan membantu proklamasi kemerdekaan. Wikana setuju.
Soebardjo, seorang Jepang, dan dua pemuda lainnya-Kunto dan Soediro-lalu menjemput Soekarno-Hatta di Rengasdengklok. Pukul delapan pagi, Kamis, 16 Agustus, dwitunggal itu tiba di Jakarta. Sepanjang hari hingga malam, Soekarno-Hatta dan Maeda berkunjung ke sejumlah perwira penting Jepang. Penguasa militer Jepang mengizinkan proklamasi disampaikan asalkan tak dikaitkan dengan Jepang dan tidak memancing rusuh. Soekarno, Hatta, Maeda, Soebardjo, Nishijima, dan dua orang Jepang lain menyusun teks proklamasi di ruang kerja kediaman Maeda di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta-kini Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
Di pihak lain, Badio dan kelompok pemuda pengikut Sjahrir pada 16 Agustus hingga tengah malam menghimpun kekuatan untuk merebut kekuasaan. Mereka juga menyiapkan naskah proklamasi versi mereka sendiri. Tapi upaya ini gagal akibat tak solid. Pagi buta 17 Agustus, sebuah delegasi yang dipimpin Soekarni menemui Sjahrir di rumah.
"Pukul tiga pagi, Soekarni memakai bot tinggi dan pedang samurai menemui saya di rumah. Ia melapor teks proklamasi menurut versi kami tidak diterima," kata Sjahrir. Soekarni juga mendesak Sjahrir ikut perundingan di rumah Maeda. "Tentu saja, tidak saya terima," kata Sjahrir.
Pukul 10 pagi, didampingi Hatta, Soekarno membacakan naskah proklamasi. Adapun Sjahrir memilih tak hadir.
Ada yang tak biasa pada Sjahrir hari itu: rautnya sumpek. Sebelumnya, si Bung baru saja bertemu dengan Soekarno, yang mengajaknya bermobil keliling Jakarta. Di jalan, Soekarno mengatakan tak secuil pun ada isyarat Jepang akan menyerah. Soekarno ingin membantah informasi yang dibawa Sjahrir sebelumnya bahwa Jepang telah takluk kepada Sekutu.
Sjahrir mengatakan ini sebelum Soekarno-Hatta berangkat ke Dalat, Vietnam, untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara. Sjahrir berkesimpulan tak ada gunanya berunding dengan Jepang. Pada 6 Agustus 1945, Jepang toh telah luluh-lantak oleh bom atom Sekutu.
Mengetahui Bung Karno tak mempercayainya, Sjahrir berang. Ia menantang Soekarno dengan mengatakan siap mengantar Bung Besar itu ke kantor Kenpeitai, polisi rahasia Jepang, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, untuk mengecek kebenaran informasi yang ia berikan. Sjahrir mengambil risiko: di kantor intel itu ia bisa saja ditangkap.
Tapi Soekarno menolak. Ia yakin Jepang belum menyerah. Itulah yang membuat Sjahrir marah meski ia tak menyampaikannya secara terbuka kepada Bung Karno.
Kepada Badiolah murka itu dilampiaskan. "Sjahrir mengumpat Soekarno man wijf, pengecut dan banci," kata Badio dalam Perjuangan Revolusi (1987). Menurut Badio, itulah marah paling hebat Sjahrir sepanjang persahabatan mereka.
Soekarno tahu Sjahrir sering memakinya. Dalam biografi karya Cindy Adams, Soekarno mengatakan Sjahrir menyalakan api para pemuda. "Dia tertawa mengejekku diam-diam, tak pernah di hadapanku. Soekarno itu gila... kejepang-jepangan... Soekarno pengecut."
Sehari sebelum Badio berkunjung, 14 Agustus 1945, Sjahrir dan Hatta menemui Soekarno di rumahnya di Pegangsaan Timur 56 dan meminta Bung Karno segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Soekarno berjanji mengumumkan proklamasi pada 15 Agustus setelah pukul lima sore. Sjahrir segera menginstruksikan para pemuda mempercepat persiapan demonstrasi. Mahasiswa dan pemuda yang bekerja di kantor berita Jepang, Domei, bergerak cepat menjalankan instruksi itu.
Tapi Sjahrir mencium gelagat Soekarno tak sepenuh hati menyiapkan proklamasi. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, badan yang bertugas menyiapkan kemerdekaan sesuai dengan permintaan Jepang, tak menunjukkan gelagat akan berhenti bekerja.
Panitia misalnya mengagendakan sidang pertama 19 Agustus 1945. Soekarno ketua dan Hatta wakil dalam panitia ini. "Ini akal-akalan Jepang," kata Sjahrir dalam Renungan dan Perjuangan. Sjahrir mengusulkan proklamasi tak menunggu Jepang. Proklamasi, kata Sjahrir, bentuk perlawanan terhadap Jepang. Inilah saatnya melancarkan aksi massa. "Aku penuh semangat. Aku yakin saatnya telah tiba. Sekarang atau tidak sama sekali," kata Sjahrir.
Pukul lima sore 15 Agustus itu, ribuan pemuda berkumpul di pinggir kota. Mereka siap masuk Jakarta segera setelah proklamasi. Begitu proklamasi disiarkan, pemuda akan langsung berdemonstrasi di Stasiun Gambir. Domei dan Gedung Kenpeitai akan direbut. Ternyata, pukul enam kurang beberapa menit, Soekarno mengabarkan belum akan mengumumkan proklamasi. Soekarno menundanya sehari lagi.
Kabar ini membuat ribuan pemuda pengikut Sjahrir marah. Sjahrir menduga polisi rahasia Jepang tahu rencana proklamasi. Para pemuda mendesak proklamasi diumumkan tanpa Soekarno-Hatta. Tapi Sjahrir tidak setuju. Ia khawatir konflik akan terjadi di antara bangsa sendiri.
Tapi kabar bahwa proklamasi batal diumumkan tak sempat dikabarkan ke Cirebon. Pemuda di Cirebon di bawah pimpinan dokter Soedarsono-ayah Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono-hari itu juga mengumumkan proklamasi versi mereka sendiri. Mereka mengatakan tidak mungkin menyuruh pulang orang yang telah berkumpul tanpa penjelasan.
Pada 15 Agustus tengah malam, Badio menemui Sjahrir. Badio mendesak Sjahrir membujuk Soekarno dan Hatta segera mengumumkan proklamasi. Sejam kemudian, Badio menemui kembali Sjahrir. Tapi, dari Sjahrir, kabar tak enak itu didengar Badio: Dwitunggal menolak menyampaikan proklamasi meski Sjahrir telah mendesak.
Pemimpin pemuda lalu pergi. Menurut Badio, mereka bertemu di Cafe Hawaii, Jakarta. Di sini mereka memutuskan untuk menculik Soekarno. Keputusan ini juga melibatkan kelompok lain, di antaranya Pemuda Menteng 31, seperti Wikana, Chaerul Saleh, dan Soekarni, serta dokter Moewardi dari Barisan Pelopor.
Sekitar pukul dua dinihari, Badio datang lagi ke Sjahrir. Ia mengusulkan penculikan Soekarno. Sjahrir tak setuju. Ia menjamin, besoknya bisa memaksa Bung Besar membaca proklamasi.
Badio pergi. Tapi satu jam kemudian ia kembali, membangunkan Sjahrir, dan mengabarkan bahwa sekelompok pemuda nekat menculik Soekarno-Hatta. Sjahrir meminta, apa pun yang terjadi, di antara mereka jangan bertikai. Yang paling penting, kata Sjahrir, proklamasi harus diumumkan secepatnya. Soekarno dalam otobiografinya menyebut Sjahrir penghasut para pemuda. "Dialah yang memanas-manasi pemuda untuk melawanku dan atas kejadian pada larut malam itu," kata Soekarno.
Dalam buku Sjahrir karangan Rudolf Mrazek (1994), Sjahrir disebut-sebut sebagai orang yang menganjurkan Soekarno dibawa ke Rengasdengklok, Jawa Barat-markas garnisun pasukan Pembela Tanah Air.
Ahmad Soebardjo, yang dekat dengan Soekarno, memberi tahu pemimpin Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang Laksamana Tadashi Maeda tentang penculikan itu. Maeda memerintahkan anak buahnya, Nishijima, mencari Wikana di Asrama Indonesia Merdeka. Nishijima dan Wikana bertengkar hebat. Nishijima memaksa Wikana memberi tahu tempat Soekarno-Hatta disembunyikan. Imbalannya: Maeda dan Nishijima akan membantu proklamasi kemerdekaan. Wikana setuju.
Soebardjo, seorang Jepang, dan dua pemuda lainnya-Kunto dan Soediro-lalu menjemput Soekarno-Hatta di Rengasdengklok. Pukul delapan pagi, Kamis, 16 Agustus, dwitunggal itu tiba di Jakarta. Sepanjang hari hingga malam, Soekarno-Hatta dan Maeda berkunjung ke sejumlah perwira penting Jepang. Penguasa militer Jepang mengizinkan proklamasi disampaikan asalkan tak dikaitkan dengan Jepang dan tidak memancing rusuh. Soekarno, Hatta, Maeda, Soebardjo, Nishijima, dan dua orang Jepang lain menyusun teks proklamasi di ruang kerja kediaman Maeda di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta-kini Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
Di pihak lain, Badio dan kelompok pemuda pengikut Sjahrir pada 16 Agustus hingga tengah malam menghimpun kekuatan untuk merebut kekuasaan. Mereka juga menyiapkan naskah proklamasi versi mereka sendiri. Tapi upaya ini gagal akibat tak solid. Pagi buta 17 Agustus, sebuah delegasi yang dipimpin Soekarni menemui Sjahrir di rumah.
"Pukul tiga pagi, Soekarni memakai bot tinggi dan pedang samurai menemui saya di rumah. Ia melapor teks proklamasi menurut versi kami tidak diterima," kata Sjahrir. Soekarni juga mendesak Sjahrir ikut perundingan di rumah Maeda. "Tentu saja, tidak saya terima," kata Sjahrir.
Pukul 10 pagi, didampingi Hatta, Soekarno membacakan naskah proklamasi. Adapun Sjahrir memilih tak hadir.












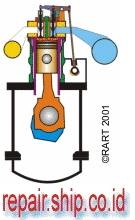




 Maret 09, 2009
Maret 09, 2009
 top
top

















